Hindari Debat Kusir Berbuntut Caci Maki, Begini Prinsip Debat Rendah Hati ala Imam Syafi’i
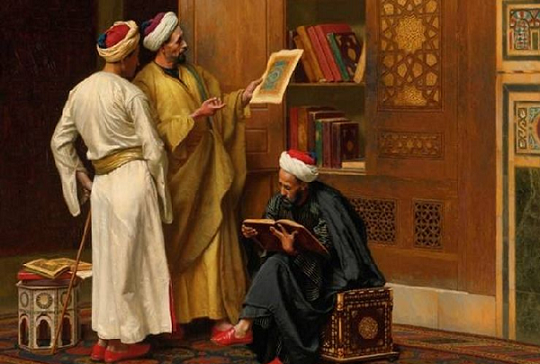
islamindonesia.id – Alkisah, di Persia ada seorang pemuda gagah dengan reputasi keilmuan yang moncer.
Meski usianya baru tiga puluh lima, namun reputasi dan kecemerlangan ilmunya di bidang bahasa dan tata gramatika Arab sangat kondang di seantero negeri. Pemuda potensial ini terkenal menjadi garda depan kajian bahasa Mazhab Basrah.
Setahun sebelum kematiannya, kepopuleran si pemuda sampai juga ke telinga Raja Harun Ar-Rasyid di Baghdad, Irak. Keluarga Barmaki yang kebetulan ada di lingkaran kekuasaan mengusulkan kepada Khalifah untuk mengundang secara khusus pemuda itu guna berdebat dengan ilmuwan-ilmuwan bahasa garda depan Mazhab Kufah.
Perlu diketahui bahwa salah satu hobi raja-raja dinasti Abbasiyah adalah mengadu ilmuwan untuk berdebat. Bahkan diceritakan bahwa raja-raja dinasti Abbasiyah menyediakan teater khusus yang dijadikan arena perdebatan bergengsi masa itu. Ilmu diadu dengan ilmu. Retorika dihadapkan dengan retorika. Argumentasi saling tindih. Demikianlah yang menjadi tradisi pada masa itu.
Di hari yang ditentukan, pemuda bernama lengkap ‘Amr ibn ‘Utsman ibn Qanbar atau yang masyhur dijuluki “Imam Sibawaih” tersebut datang ke arena perdebatan. Tidak tanggung-tanggung, sang pemuda datang sendirian dan berhadapan dengan sebuah regu ilmuwan yang terdiri dari tiga orang: Al-Kisa’i, Al-Farra’ dan Khalaf al-Ahmar. Kecuali Khalaf al-Ahmar, dua penantang memiliki usia yang sudah cukup lanjut, setingkat usia menjelang pensiun.
Perdebatan antar-dua kelompok ini kemudian hari menjadi sejarah yang sangat populer di kalangan ilmuwan ahli bahasa dan tata gramatika Arab.
Meskipun adu argumen kedua kelompok berimbang, perdebatan berakhir di tangan kadi kerajaan yang putusannya memenangkan pihak penantang yang terdiri atas tiga orang tersebut. Itulah keputusan yang belakangan dinilai sangat politis karena ada unsur ketidakadilan di dalamnya.
Sejarah perdebatan itu dikenal dengan perdebatan Mazhab Bashrah dan Mazhab Kufah dan direkam dengan sangat bagus oleh Ibnu Hisyam dalam kitab “Mughni Labib” yang diterbitkan pada abad ke-8.
Hal yang sama juga pernah dialami Imam Syafi’i. Ia berdebat semalaman dengan murid Imam Hanafi bernama Muhammad Ibnu Hasan asy-Syaibani. Adu argumentasi dan juga analisis ilmiah berhamburan dalam perdebatan itu.
Bahkan Imam Syafi’i diceritakan meninggal beberapa hari setelah menjalani perdebatan yang melelahkan dengan seorang ahli fikih dari Mazhab Maliki bernama Asyhab al-Qaisi.
Berbeda dengan Imam Syafi’i yang tetap mampu menjaga kesantunan dan emosi, lawan debatnya, Asyhab, lantaran kesal dan jengkel dengan perdebatan yang sengit itu, diceritakan sampai menggebrak meja dan melempar Imam Syafi’i dengan sebuah kunci.
Tradisi berdebat dan adu argumen merupakan salah satu di antara dua alat penguji kealiman seseorang dalam tradisi Islam yang sudah berlangsung ratusan tahun.
Selain perdebatan, Islam mengenal tradisi uji transmisi atau sanad. Kualifikasi kealiman bukan saja diuji dari kepiawaian berargumentasi, namun lebih dari itu diuji dengan ketersambungan transmisi keilmuan.
Tradisi perdebatan juga merupakan tradisi intelektual Islam. Dengan perdebatan, selain katup-katup ketidakpahaman yang menyumbat cara pandang bisa terbuka dan membuat khalayak semakin tercerahkan, lebih dari itu juga bisa memupuk kedewasaan.
Nah, soal yang disebut belakangan inilah salah satu efek terpenting yang mesti dihasilkan dari tradisi perdebatan yang baik.
Kedewasaan umat bisa diukur salah satunya melalui seberapa lapang menerima perbedaan. Dan untuk menumbuhkan sikap kedewasaan, tidak ada jalan lain kecuali terus membangun tradisi perdebatan yang dialogis, bukan monologis.
Mirip ungkapan “pelaut yang tangguh tidak terlahir dari lautan yang teduh”, umat yang dewasa tidak tumbuh dari iklim yang tidak biasa berdebat dan menerima pandangan-pandangan berbeda.
Prinsip ini pula lah yang dipegang teguh oleh Imam Syafi’i ketika dia menyatakan: “Aku tak pernah berdebat dengan siapa pun seraya berharap mereka salah…. Aku tak pernah bicara dengan siapa pun kecuali aku ingin dia dalam kebenaran dan kebaikan. Dan aku tak pernah bicara dengan seorang pun kecuali aku berharap Allah meletakkan kebenaran pada lisanku atau lisannya.”
Itulah prinsip yang selalu dipegang teguh Imam Syafi’i. Padahal seperti kita ketahui, dia adalah salah seorang di antara imam mazhab yang terkenal alim dan jago dalam berdebat. Bahkan, ulama yang lahir di Gaza pada 150 H dan wafat di Mesir 204 H ini dikenal sebagai mujtahid mutlak dengan beberapa karyanya antara lain Al Umm (fikih), Ar Risalah (ushul fikih), dll.
Tidak diragukan lagi bahwa Imam Syafi’i amat akrab dengan perdebatan, dan beberapa ulama besar pun pernah terlibat perdebatan dengannya, seperti Muhammad bin Al Hasan, Syeikh ahlu ra’yi, sahabat sekaligus “ustaz” Imam Syafi’i sendiri, juga Asbagh bin Al Farj bin Sa’di, faqih dari kibar ulama mazhab Maliki di Mesir, begitu pula pernah berdebat dengan Imam Ahmad bin Hambal tentang kekufuran mereka yang meninggalkan shalat.
Akan tetapi setiap berdebat dengan ulama lain ia selalu menggunakan adab dan sopan santun serta tidak sekali pun mencela lawannya.
Adalah Abu Utsman, putranya pernah mengatakan: “Aku sekali-kali tidak pernah mendengar ayahku mendebat seseorang dengan meninggikan suaranya.” (Tahdzibul Asma’ Wal Lughat, hal. 66, vol.1).
Ahmad bin Kholid bin Kholal berkata: “Aku mendengar Syafi’i berkata, “ketika aku mendebat seseorang aku tidak menginginkan dia jatuh kepada kesalahan.” (Tawaliyut Ta’sis, hal. 65)
Syafi’i sendiri juga pernah berkata: “Aku berdebat tidak untuk menjatuhkan orang.” (Tahdzibul Asma Wal Lughat, hal. 66, vol.1)
Hafidz Ad Dzahabi menukil di Siar A’lamin Nubala’, dari Imam Hafidz Abu Musa Yunus bin ‘Abdul A’la Ashodafi Al Misri, salah satu sahabat Imam Syafi’i, dia berkata: “Aku tidak melihat orang berakal melebihi Syafi’i, aku mendebatnya tentang suatu masalah pada suatu hari, kemudian kami berpisah, lalu dia menemuiku, dan menggandeng tanganku, lalu berkata: “Wahai Abu Musa, bukankan lebih baik kita tetap berteman walau kita tidak sepakat dalam satu masalah?”
Berkata Imam Ad Dzahabi: “Ini menunjukkan kesempurnaan akal imam ini, dan paham atas dirinya…” (Siar A’lam An Nubala’ hal. 16, vol. 10).
‘Alamah Murtadha Az Zabidi berkata dalam Syarh Ihya’ ketika Imam Ghazali membahas tentang perdebatan-perdebatan para salafus shalih, bagaimana hal itu terjadi di antara mereka, bagaimana mereka mempertahankan al haq dengan adab dan sopan santun, berkatalah Murtadha Az Zabidi: “Salah satu di antaranya adalah perdebatan Ishaq bin Rahuyah dengan Imam Syafi’i, dan Ahmad bin Hambal hadir pula di tempat itu, aku telah membaca dari Kitab Nasikh Wal Mansukh, karya Hafidz Abu Al Hasan Badali bin Abil Ma’mar At Tibrizi: “…Dikisahkan bahwa Ishaq bin Rahuyah mendebat Syaf’i, dan Ahmad bin Hanbal ada di tempat itu juga, tentang hukum kulit bangkai jika disamak. Maka, berkatalah Syafi’i: “Jika disamak maka menjadi suci.” Maka berkatalah Ishaq: “Apa dalilnya?” Maka Syafi’i menjawab: “Hadis Az Zuhri dari ‘Ubaidillah bin Abdullah bin Abdullah, dari Ibnu ‘Abbas, dari Maimunah, bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tidakkah kalian memanfaatkannya dengan cara menyamaknya?”
Maka berkatalah Ishaq kepadanya: “Hadis Ibnu ‘Ukaim: “Rasulullah s.a.w. telah menulis untuk kami, kira-kira sebulan sebelum beliau meninggal, “Jangan memanfaatkan sesuatu dari bangkai dengan, baik kulitnya maupun dagingnya.” Hadis ini sepertinya memansukh hadis Maimunah, karena datang satu bulan sebelum wafat”.
Maka berkatalah Syafi’i: “Ini tulisan dan tadi (hadis Maimunah) ucapan.” Ishaq menjawab: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. menulis untuk Kisra dan Qoishar, dan hal itu hujjah di antara mereka di hadapan Allah, dan diamlah Syafi’i.
Dan ketika Ahmad bin Hambal mendengar hal itu, dia memilih hadis Ibnu ‘Ukaim dan berfatwa dengannya, dan sebaliknya Ishaq malah condong kepada hadis Syafi’i.
Berkata Abu Al Hasan At Tibrizi: “Khalal telah mengisahkan dalam kitabnya, bahwa Ahmad bin Hanbal tawaquf terhadap hadis Ibnu ‘Ukaim ketika melihat tazalzul (kegoncangan) dalam periwayatannya, dan ada beberapa yang mengatakan bahwa Imam Ahmad meninggalkan hadis tersebut.”
Cara inshaf dalam masalah ini adalah, bahwa hadis Ibnu ‘Ukaim kalau dilihat secara dhahir memang menunjukan nashk jika sahih, akan tetapi hadis tersebut itthirab (guncang), maka dia tidak sebanding kesahihannya jika dihadapkan dengan hadis Maimunah, berkata Abu ‘Abdurrahman An Nasai: “Yang paling sahih dalam masalah ini adalah hadis Maimunah.” (Syarhul Ikhya’, hal.291, vol.1)
Abdul Fattah Abu Ghuddah mengomantari nukilan di atas: “Lihatlah, inshaf Ishaq yang meninggalkan pendapatnya setelah jelasnya kebenaran, dan adab Syafi’i dan tawadhu’nya, di mana ia diam ketika terlihat kebenaran atas pendebatnya.”
Adapun berkenaan dengan etika dakwah, Imam Syafi’i juga menganjurkan agar ditempuh dengan cara sopan dan adab mulia, dengan rendah hati dan bukan dengan debat kusir yang tak jelas ujung pangkalnya.
Meyakini bahwa dakwah itu semata untuk kebaikan dan niat meraih kebaikan, perhatikan betapa tawadhu-nya Imam Syafi’i, saat dia berkata:
مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إِلا عَلَى النَّصِيحَةِ
“Tidaklah aku mendebat seseorang melainkan dalam rangka memberi nasihat.” (Adabu Asy-Syafi’i wa Manaqibuhu, hal. 69)
Begitu pula saat dia berkata:
وَاللَّهِ ، مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُخْطِئَ
“Demi Allah, tidaklah aku mendebat seseorang melainkan berharap akulah yang keliru.” (Tabyinu Kadzbil Muftari, hal. 340)
Semoga kita semua senantiasa Allah SWT karuniai kemampuan untuk mengikuti jejak para ulama tawadhu seperti Imam Syafi’i, sehingga tidak mudah larut dalam perdebatan panas yang kemudian berbuntut saling hina dan caci-maki, sebagaimana kerap kita temui, terutama di ranah media sosial belakangan ini.
EH/Islam Indonesia

Leave a Reply